Pejalanan pulang melalui jalur darat selesai menunaikan haji. Pilihan
kami ini bukan tanpa alasan, guru kami pernah berpesan; kalau pun harus
terbang jangan sampai hal itu membuatmu merasa tinggi.
Ingatlah bahwa di bawah sana banyak kekasih-kekasih Allah yang
hidupnya sederhana. Selain itu, perjalanan darat menawarkan kepada kami
tentang rihlah sejarah.
Jalur yang kami lewati antara kota suci
Mekah dan Tarim melalui kota tua Sana’a, ibu kota Yaman, dan tempat
bersejarah lainya seperti daerah Darwan yang terletak di sebelah barat
daya Sana’a. Daerah Darwan oleh para pakar sejarah Islam diperkirakan
adalah daerah pemukiman Ashabul Jannah yang disebut-sebut Allah dalam
dalam kitab suci Nya. Konon, Darwan memiliki kwalitas tanah tersubur
yang berada di muka bumi, sehingga tidak sedikit buah-buahan, kurma,
anggur, dan berkah bumi lainnya dihasilkan dari daerah tersebut.
Pagi
hari kami telah melewati perbatasan. Kala itu, urusan imigrasi di
perbatasan rada tersendat, tampaknya ada sedikit masalah dengan paspor
kami, sebelum akhirnya uang dapat mempermudah urusan. Dari perbatasan ke
Sana’a kami menyewa travel. Biaya yang ditawarkan si sopir cukup mahal,
yaitu 15 dinar. Satu dinar pada saat itu senilai sama dengan sekitar 75
ribu rupiah, atau sekitar 30 riyal. Namun setelah jadi tawar-menawar
yang cukup ulet, si sopir menurunkan 1 dinar per orang. Aku, Xafi dan
Umar, masing-masing membayar 120 riyal.
Travel yang kami
tumpangi tak lain adalah mobil SUV tua peninggalan penjajahan Rusia.
Mula-mula kami ragu, namun setelah berjalan beberapa saat kemudian kami
mulai menikmati. Ternyata mobil Eropa sangat nyaman walaupun segi fisik
terlihat usang. Di luar dugaanku, mobil sangat cepat melibas jalanan,
terkadang juga harus melintasi gurun untuk menempuh jalan pintas. Masih
sekuat mobil-mobil Rally Paris Dakkar yang sering aku lihat di televisi
dulu.
Debu-debu mengepul di sisi kanan-kiri kaca, sesekali mobil
melakukan jumping ketika menabrak gundukan-gundukan kecil. Suspensi
yang masih baik membuat kami tidak begitu merasakan benturan yang keras
di dalam mobil.
Ketika aku mulai berbicara heart to heart,
menceritakan tentang masa laluku, Xafi akhirnya mulai terbuka. Ia kali
ini tidak lagi menghindar dari pertanyaanku. Sepanjang perjalanan ia
bertutur tentang masa lalunya yang penuh dengan kegelapan dan
kebimbangan, sebelum akhirnya datang petunjuk Tuhan.
“Aku tidak
tahu bagaimana mulanya. Saat itu umurku menginjak 15 tahun, seperti
kebanyakan remaja lainnya di negeriku, aku hidup dalam kebebasan dan
mulai berani mengekspresikan hayalan liar. Aku tidak tahu siapa ayahku.
Aku hanya tinggal bersama ibuku di sebuah apartemen tua. Pada suatu
malam aku bermimpi mendengar sebuah nyanyian, namun entah nyanyian apa
itu? Semacam bunyian-bunyian akapela, kedengaran seperti paduan suara di
gereja-gereja.”
“Semenjak itu, mimpi yang sama sering hadir
dalam tidurku. Semakin sering terjadi aku semakin penasaran. Ada satu
lirik yang aku coba ingat, dan lirik itulah yang kemudian aku tanyakan
kepada ibuku. Namun ibuku tidak tahu. Aku coba bawa masalahku ini ke
sekolah dan aku tanyakan kepada guruku. Tapi apa jawaban yang kudapat?
Katanya aku mengalami gangguan jiwa. Aku disarankan menajalani terapi.
Aku merasa baik-baik saja. Aku tak merasa menyimpang dari sebelumnya,
selain aku mulai malas datang ke gereja, dan bagiku itu wajar, seperti
kebanyakan teman sebayaku yang mulai kenal dengan kehidupan luar. Tak
sengaja ada seorang guru sejarah yang mendengar masalahku. Ia kemudian
menemuiku dan menjelaskan apa yang sebenarnya kualami.
“Nak, lirik itu adalah bunyi-bunyian dalam Islam,” jelasnya tentang apa yang kudengar dalam mimpi.
“Ya,
aku tahu ada Agama Islam, tapi aku tak tahu kalau ada suara seindah itu
dalam Islam. Lalu aku tanyakan kembali, “Sesungguhnya apa yamg kudengar
ini, Pak? Lagu, novel, atau apa?”
Guru sejarah itu tersenyum kecut, “Lupakan saja. Itu hanya nyanyian peperangan, dalam sejarah kelam bangsa kita!”.
Di
lain hari aku menemui seorang biarawan, aku rasa dialah yang alim dalam
urusan agama. Barangkali ia pernah mendapat pelajaran tentang
perbandingan agama, dan pasti dia sedikit banyak tahu tentang Islam, dan
tentunya ia tahu lagu apa yang sering kudengar dalam mimpiku. Biarawan
itu kaget mendengar pertanyaanku.
“Baiklah, akan aku beritahu.
Mimpimu adalah sadarmu, dan yang kau dengar itu sebenarnya bukan
nyanyian, melainkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an, seperti Injil dalam agama
kita. Ayat yang kau dengar itu menerangkan tentang siapa Tuhan menurut
agama mereka? Allah adalah Tuhan, dan yang disebut Tuhan pastilah baik.
Hanya saja konsep Tuhan menurut kita beda dengan konsep Tuhan menurut
mereka yang cuma satu.”
Nak, kata guru sejarah, mimpimu itu adalah teguran dari Tuhan agar kau rajin-rajin beribadah!
Setelah
mendapat jawaban dari biarawan itu, aku mulai belajar tentang Islam.
Sampai akhirnya aku benar-benar yakin. Dua tahun kemudian aku pergi ke
Casablanca untuk meresmikan keyakinan baruku. Aku mengucapkan Syahadat
di bawah bimbingan seorang Syeikh. Dan Sekarang, ya seperti yang kau
lihat sendiri, dan Alhamdulillah aku sudah menenuaikan rukun ke lima ini
bareng Kamu” Begitulah kira-kira cerita Xafi yang bisa kutangkap.
“Lega bukan rasanya sudah menenunaikan kewajiban?” tanyaku mengomentari ceritanya.
“Belum.” Xafi kulihat membuang pandangannya ke luar mobil.
“Kenapa?” tanyaku kembali.
“Aku
selalu berdoa, agar ibuku mendapat petunjuk!” Xafi lalu diam. Suaranya
agak serak ketika menjawab pertanyaanku. Dan aku, tahu, semua orang
pasti ingin ibunya bahagia.
Umar yang mengajak pulang naik
pesawat rupanya sangat kesal karena aku dan Xafi memilih perjalanan
darat. Sepanjang perjalanan ia hanya diam, cemberut. Mungkin karena aku
tidak memihak kepadanya. Aku bisa memaklumi. Namun aku sengaja
memberinya pelajaran seperti ini. Biar dia tidak mudah menghina
orang-orang miskin.
Mobil berhenti di kota Harad untuk mengisi
bahan bakar. Si sopir memberi kami waktu sebentar untuk membeli
perbekalan, atau sekadar istirahat sejenak. Karena setelah ini kami akan
menempuh perjalanan yang sangat panjang, ratusan mil jauhnya. Melewati
gurun sahara, padang pasir yang tak bertuan, dan lembah-lembah yang
sangat tandus. Mungkin senja hari kami baru sampai di kota Hamr, itu pun
jika tidak terjadi gangguan dalam perjalanan, seperti ban kempes dan
lainnya. Kami gunakan jeda tersebut untuk mandi. Betapa segarnya yang
kurasa, tubuh tidak lagi terasa gerah. Plikat-plikat keringat telah
luruh dibasuh air suci. Umar lalu pergi ke rumah makan untuk membeli
perbekalan, barangkali roti dan air minum. Aku dan Xafi melakukan
relaksasi sejenak dengan saling memijat bergantian.
Tidak sampai
satu jam kami istirahat si sopir mengajak kami untuk melanjutkan
perjalanan. Kota Harad tidak begitu besar, namun kota Harad adalah
satu-satunya kota yang paling besar yang kami lewati semenjak dari
perbatasan. Dari kota ini mobil mendapat tambahan satu penumpang. Ia
duduk di depan bersama sopir, sedangkan kami tetap pada posisi semula.
Mobil
berjalan meninggalkan kota, lalu desa dan lepas meninggalkan pemukiman.
Dari balik kaca depan mobil yang tampak hanya genangan air yang
menggeliat di atas permukaan tanah. Sebenarnya aku kasihan pada Umar.
Aku yang kurus saja merasa gerah, apalagi dia. Tapi bagi saya pribadi,
perjalanan ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Bagai suku-suku
Arab nomaden dalam melakukan surfive kehidupan. Ada banyak sejarah,
tetesan keringat dan darah yang perlu aku renungi dari perjuangan islam
sepanjang perjalanan ini. Beginikah rasanya mereka dahulu dalam
menyebarkan agama? Memangkas potongan-potongan siksa untuk menebarkan
pahala. Sungguh, aku merasa tidak ada apa-apa, bahkan debu yang mereka
injak pun aku tak sebanding.
Perasaan jenuh gerah dan yang tak
enak-enak sudah mulai berdatangan, namun kota Hamr masih jauh di ujung
mata. Bosan memang membosankan, tapi di saat seperti inilah saat yang
tepat untuk melatih kesabaran. Bau tak sedap keringat bercampur kunyahan
daun ghot penumpang dari Harad menambah memperburuk suasana. untung
saja dulu aku sudah terlatih dengan semacam ini ketika naik kereta
ekonomi jurusan Jakarta. Hanya saja panas dan debunya tak separah di
sini.
Di tengah-tengah perjalanan kami berhenti sebentar untuk
melaksanak shalat Jamak Ta’khir, dhuhur di waktu ashar. Mobil menepi,
dan semua penumpang turun. Kami mengambil air wudlu dari sebotol aqua
ukuran 1,5 mili liter yang telah kami persiapkan sebelumnya. Hanya
sebentar mobil kebali berjalan. Suasana sudah tak sepanas sebelumnya.
Satu jam perjalanan nampak mentari mulai menuruni balik bukit dan mulai
menjauhi arah laju mobil.
Di depan jauh sana aku melihat seperti
ada sesosok manusia berjalan. Aku perhatikan benar siluet tersebut. Jika
benar-benar orang, mungkin dialah satu-satunya pejalan kaki yang kami
temui di sepanjang perjalanan. Aku mulai yakin ketika mobil semakin
dekat. Nampaknya seorang wanita sebatang kara. Entahlah apa ia
tertinggal dari rombongannya, atau penduduk setempat? Tapi sepanjang aku
memutar mata, tidak kudapatkan pemukiman di sekeliling jalan yang kami
lalui.
Mobil melintasinya perlahan. Dari dalam aku melihat wanita
itu berjalan sempoyong tak berdaya. Seketika hatiku terketuk tak tega.
Aku meminta sopir untuk berhenti, pedal gas diinjaknya dalam, dan ban
menggasut tanah liat memunculkan asap debu.
Aku bergegas turun menghampirinya.
“Assalamualaikumm..”.
“Salamun qaulan min rabbir rahim..”[1] jawab wanita itu atas salam yang kuucapkan.
“Yarhamukillah.. wahai fulanah, apa yang kau perbuat di tempat seperti ini?”
“Wa man yudllil fala haadiya lah!”[2] jawabnya.
“Maksudmu apa?”
“Wa man yudllil fala haadiya lah!”[3] Jawaban sama yang kudapatkan darinya.
Aku
tidak paham. Lalu memanggil Xafi untuk membantu menanyainya. Xafi turun
dari mobil dan berdiri di sampingku. Tapi tetap saja wanita itu
menjawab dengan kalimat yang sama “Wa man yudllil fala haadiya lah!”[4]
Xafi yang cerdas segera tanggap dengan jawaban tersebut. “Mungkin
maksudnya: dia sedang tersesat!”
“Emm..baiklah. terus antum hendak kemana?” tanyaku lagi kepada wanita itu.
“wa
atimmulhajja wal ‘umrata lillah… fa man lam yajid fashiyamu tsalatsati
ayyamin filhajji wa sab’ati idza raja’tum..ala bu’dan li’adin qaumi
hud…”[5] jawabnya.
Xafi tampak berpikir memahami jawaban wanita
itu, lalu setelah mendapatkan ia coba menjelaskan kepadaku. “Mungkin
maksudnya; ia baru saja menunaikan ibadah haji, dan sekarang ia dalam
perjalanan pulang ke rumah yang kemungkinan berada di sekitar Syi’eb
Hud.”
Aku mulai memahami cara berbicara wanita ini. Dia selalu
menggunakan ayat-ayat Al- Qur’an dalam memberikan jawaban. Ini seperti
bermain sanepo. Tidak ada jawaban yang diutarakan secara langsung.
Untung saja xafi mudah tanggap dengan jawabannya.
“Wahai Fulanah,
mengapa kau tak menjawab dengan biasa? Bisakah kau berbicara sepertiku?
Maksudku dengan bahasa percakapan.” Aku membujuk agar dia tak lagi
menggunakan bahasa Sanepo, dan percakapan kami dapat berlangsung dengan
mudah.
“ma yulfadzu min qaulin illa ladaihi raqibun ‘atiid….”[6]
Astaghfirullah..
jawaban yang mematikan, aku menyerah. Sudahlah, aku tidak bisa memaksa
orang untuk memahamiku, tapi bagaimana sebaiknya aku sekarang bisa
memahaminya.
“Anda berasal dari mana?” lanjutku.
“wa la taqifu ma laisa laka bihi..”
“cukup..cukup” putusku. Aku semakin pusing dengan jawabannya yang tidak membantu.
Baiklah,
begini saja. Beri aku jawaban yang mudah, agar aku bisa menolong, atau
setidaknya membantumu?! Ee, sudah berapa hari anda tersesat?”
“tsalatsa layalin sawiyya; .” [7]
Hah, tiga hari?!
“Emm, kelihatannya kau kehabisan makanan?”
“Huwa yuth’imuni wa yasqin: .”[8] jawabnya seolah tak perduli.
Sebenarnya aku sebal dengan percakapan yang kaku ini. Tapi aku tak tega melihatnya.
Aku
coba menggiring percakapan ini ke yang lebih baik, tentunya untuk dia.
Bagaimana dia sudah tiga hari tersesat di gurun tanpa tersisa bekal.
Akan tetapi bagaiman aku bisa membantunya jika percakapan masih
berlangsung seperti ini.
“Maukah kau kuambilkan makan dan minuman?”
“Tsumma atimmus shiyama ilal laili”[9]
Penolakan
yang halus. Tapi aku berusaha membujuknya untuk menerima bantuan dari
kami. Baiklah jika dia ingin berpuasa, tapi apakah dia tidak memikirkan
kondisi tubuhnya yang sudah tak berdaya seperti itu.
“Tapi sekarang bukan bulan Ramadan!” bujukku.
“wa man tathawwa’a khairan fa innallaha syakirun ‘alim..”[10]
“Hemm.. pintar! Tapi bukankah kita diperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan!” desakku.
“wa
an tashumu khairun lakum in kuntum ta’lamun..”[11]Lagi-lagi hujah yang
ia katakan membuatku mati kutu. Mendengar jawaban-jawaban yang tak
membantu itu xafi menyuruhku untuk meninggalkan saja. Aku sendiri masih
bimbang.
“Baik lah.. mohon maaf jika kami telah menganggu perjalanan anda? Sekali lagi mohon maaf..”
“La
tatsriba ‘alaikum alyauma yaghfirullahu lakum….. la tatsriba ‘alaikum
alyauma yaghfirullahu lakum….. la tatsriba ‘alaikum alyauma
yaghfirullahu lakum..///”[12]
Begitu aku mendengar dia
memaafkanku dengan cara yang sama, hatiku tiba-tiba tersentak. Ini orang
bukan sembarangan, pikirku. Jarang sekali orang berbicara demikian.
Al-Qur’an dan Al-Qur’an, tidak ada yang lain.
Aku yang sebenarnya
sudah mulai putus asa timbul niatan untuk memberinya tumpangan. Tapi
aku tidak berhak sepenuhnya atas itu. Jadi aku perlu minta ijin lebih
dahulu pada si sopir, dan penumpang lainnya. “Itu terserah kamu? Tapi
apa yang lainnya setuju?” kata Xafi. “Mangkanya itu?” jawabku lalu
menemui si saik. “Asalkan membayar? Sepuluh orang pun boleh?” katanya.
Tapi rupanya temanku yang satunya lagi keberatan. Aku memaklumi karena
Umar memang orang yang kaku, kolot, cenderung fundamentalis dalam
bermazhab.
“Ini bukan soal mahrom dan tidak. Juga bukan soal
halal haram, Mar! Cobalah sedikit lebih toleran..! Ini soal nyawa
perempuan itu, Mar?!”
“Tetap saja tidak bisa!” jawab Umar bersikukuh pada pendiriannya.
“Baiklah, kalau tidak boleh, aku dan saleh akan tetap tinggal!” kata Xafi membelaku.
“Oh,
jangan.. jangan..!” Umar ketakutan. Karena ia sebenarnya jarang
bepergian dan takut bila sendiri. “Ya sudah.. Tapi jangan kau dudukkan
wanita itu bersamaku!”“Kebetulan,” kata hatiku.
Xafi nyengir. Umar cemberut membuang mukanya ke kaca sebelah. Aku lalu menghampiri wanita tersebut untuk menawarkan tumpangan.
“Maukah kau ikut bersama kami?” kataku menawari.
“wa ma taf’alu min khairin ya’lamhullah; ..”[13] jawabnya berkali-kali.
Niat yang tidak sia-sia, besitku dalam hati.
Akhirnya
dia menerima tawaranku. Aku mengajaknya ke mobil. Aku bukakan pintu.
Lalu wanita itu segera masuk. Tanpa sengaja ketika naik kepala wanita
itu terbentur ke dinding pintu. “Inna lillahi..” wanita itu terjatuh ke
tanah. Jubahnya semakin penuh dengan balutan debu. Ia berusaha bangkit
sendiri. Aku semakin tak tega.
“Wa ma ashabakum min mushibatin fa bima kasabat min aidikum;..” ujarnya sambil meraih badan mobil untuk bangkit.
“Ishbirii, Ya ukhti..”[14]
“Fa fahimnaha sulaiman;..”[15] balasnya santun.
Aku mempersilakan ia kembali masuk ke dalam mobil.
“Qul
lil mu’minina yaghudldlu min absharihim;..”[16] perintahnya menggunakan
perintah Tuhan. Ia sepertinya mau membuka khimar yang menghalangi
pandangannya.
“Baiklah, kami akan memejamkan mata. Silakan masuk, Ya Ukhti!”
Saat aku buka mata wanita itu telah berada di dalam mobil. Aku segera masuk menyusulnya. Si sopir menjalankan mobilnya kembali.
“Subhanalladzi
sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina
lamunqalibun;..”[17] ucap wanita itu di awal laju.
Xafi yang
berpindah di jok belakang melantunkan Qasidah dari diwan haddad
kesukaannya. Suaranya begitu merdu, meliuk-liuk serupa seruling. Tapi
entah mengapa wanita itu tidak begitu suka, dan menghentikan dengan
membaca ayat “waqshid fi masyika waghdluld mis shautik.. waqra’uu ma
tayassara minal qur’an;…”[18]
Xafi berhenti bersenandung, dan si
saik memelankan laju mobilnya. Aku menengok ke belakang, kulihat umar
semakin cemberut. Aku senang, setidaknya ia mau toleran dengan sesama
umat manusia. Hehehe, aku tersimpul di samping wanita itu, di dalam
mobil yang melaju yang terasa nyenyap, tidak ada qasidah yang
disenandungkan, tidak ada diantara kami yang hafal alqur’an, sedangkan
wanita itu sendiri juga diam.
“Apakah anda sudah mempunyai suami?” Tanyaku coba mencairkan suasana.
“Ya ayyuhalladzina amanuu la tas`aluu ‘an asyya`a in tubda lakum tasu`kum:..”[19]
Hehehe..
Aku sudah kehabisan akal untuk mencari cara. Lagi-lagi ayat-ayat
Al-Qur’an yang ia lantunkan bagai senjata mematikan. Dan hal itu juga
membuatku semakin yakin akan mukjizat Al-Qur’an dalam mengalahkan lawan
bicara.
Kami semua diam seiring mentari tenggelam. Mobil
merangkak di atas jalanan padang pasir, bagai siput menuju kota Himr.
Kesunyian semakin bertambah ketika langit semakin gelap. Tidak ada suara
lain di dalam keheningan senja, kecuali derum mobil yang menabuh
dinding penjuru. Diantara kesepian itu, sesekali terdengar si saik dan
penikmat daun ghot berbincang-bincang dengan bahasa yang tak kupahami.
Bahasa arab dalam intonasi mereka terdengar seperti bahasa madura saja,
membuatku geli ingin tertawa, tapi kutahan, aku takut mengganggu
ketenangan wanita di sampingku. Setelah yakin memasuki waktu Maghrib aku
tawarkan air dan roti. Ia menerimanya. Aku minta kepada umar untuk
berbagi madu dengan wanita itu. Barangkali rasa manis dapat membantu
mengembalikan staminanya.
Sungguh banyak sekali orang di negeriku
yang hafal Al-Qur'an, namun sedikit sekali yang seperti dia. Aku
teringat kata Alhabib; Al yamanu ilmu wal amal. Yaman adalah tempat ilmu
dan amal. Mungkin karena itu orang di negeriku tidak, atau belum ada
yang sepertinya.
Ketika sampai di pemukiman kami segera mencari
kafilah, barangkali ada diantara mereka yang mengenal perempuan yang
bersama kami. Kami sadar bahwa dia tidak bisa berlama-lama bersama kami.
Dalam budaya dan tradisi arab perempuan yang bukan muhrim tidak mungkin
bersama lelaki lain, kecuali dalam keadaan memaksa (dlarurat). Maka aku
minta kepada si saik untuk membawa kami ke penginapan yang ada di desa
tersebut. Setelah bertanya pada penduduk setempat mobil bergerak pelan
menuju ke tengah-tengah pemukiman, tempat satu-satunya penginapan itu
berada.
“Ya Fulanah! Adakah kau mempunyai seseorang yang bisa aku hubungi?” Tanyaku dalam bahasanya.
Perempuan
yang sampai saat ini belum ku tahu namanya itu hanya mengangguk. “pelit
amat kau!” besitku dalam hati. Sungguh padahal di negeriku ada pepatah;
barang siapa malu bertanya maka sesat di jalan. Ini orang sudah
tersesat, masih pelit bicara. Aduh, pasti orang seperti ini di negeriku
akan selamanya tersesat. Bukan karena dia tidak baik, melainkan apalagi
di daerah sumatera, konon orang yang paling baik adalah orang yang
menyesatkan penanya jalan.
“Siapa?”
“Wa qad Ahsana bii idz
akhrajanii min assijni wa ja~a bikum min albadwi min ba’di an nazagha
asysyaithanu bainii wa baina ikhwatii”[20]
Dengan jawaban
tersebut aku tahu kalau dia terpisah dari saudaranya dalam perjalanan.
Tidak mungkin orang yang ketat beragama seperti orang-orang Yaman macam
dia keluar dari rumah sendirian, seperti yang sudah menjadi kebiasaan
perempuan di negeriku, itu tidak mungkin. Setiap kali
perempuan-perempuan Hadramiy itu keluar dari sarangnya, pasti ada satu
dua keluarga yang menyertai, entah itu ayah atau saudara lelakinya. Tapi
ia tidak menyebutkan siapa saudaranya itu.
“Adakah nama yang bisa aku gunakan untuk memanggil saudaramu, Ya Fulanah?”
Mendengarku
mengulang pertanyaan aku berharap kali ini yang keluar dari mulutnya
adalah sebuah nama, dan bukan teka-teki ayat yang harus membuatku
berpikir terlebih dahulu untuk menangkap jawaban. Ia segera menjawab,
tapi suara bising mobil menelan mentah-mentah suaranya yang rendah dan
pelan itu.
“Ma? Qul jahran Ya Fulanah!” bentak Umar tidak sabar.
Wanita
itu sedikit terkaget dengan suara keras umar, sembari memagangi jantung
lalu mengulangi jawaban. Kali ini dengan suara yang cukup keras untuk
kami dengar.
“Wa attakhada Allahu Ibrahima khalila…. Ya Yahya khudzi alkitaba bi quwwah.”[21]
Hemm..
Aku kira dia akan menyebutkan namanya saja, namun ternyata nama
saudaranya itu juga ada dalam deretan ayat-ayat kitab suci. Aku
memandang Umar, umar mengangguk. “Yahya dan Ibarahim,” lanjutku.
“Mungkin?”
“Coba kau cari di penginapan!” ujarku kepada Umar.
“Ah, tidak. Kau saja yang keluar!” kelitnya.
“Banci!”
“Ma huwa banci?” Tanya Xafi atas bahasa asing kami.
“Banci ‘inda lughatil arab; khuntsa, ya Xafi!” jelasku
Xafi tertawa mendengarnya.
“Amma inda lughat Asbaniyyah: Afimanado” lanjut Xafi memberi dalam bahasa Spanyol.
“Tak pantas kau bernama Umar! Lebih baik jika kau kujuluki Afimanado, benarkan seperti itu?”
“Na’am.. Afimanado. Hahaha” Xafi tertawa terpingkal-pingkal.
“Kenapa tak pantas?” tampik Umar nampak marah ditertawakan.
“Memang
tak pantas. Umar itu nama seorang yang pemberani, bukan cuman keras
doank! Kalau Cuma keras, Abu Lahab juga keras, alias kolot!”
Umar
melawan, mencoba membantah tuduhanku atas dirinya. Dia coba memintaku
untuk diam di dalam mobil. Xafi melerai percekcokan kami. Tapi aku tak
hiraukan, lalu keluar menuju penginapan. Si sopir menyusul di
belakangku, dan mendahuluiku ketika masuki pintu penginapan.
Perasaanku
sangat jengkel terhadap Umar. Aku suka orang yang teguh dalam beragama,
keras dalam mempertahankan prinsip, tapi aku tak suka dengan orang yang
‘sok’ seperti Umar. Teramat jauh perangainya bila dibandingkan dengan
Umar yang habib, guru kami. Umar ini bisanya cuma meniru kerasnya saja,
tidak alim apalagi saleh. Beda dengan guru kami, keteguhannya mendasar,
murah senyum dan murah hati dengan umat, kendati berdisiplin keras akan
tetapi untuk pribadi dan keluarganya sendiri.
Seorang syeikh yang
mempunyai penginapan tersebut keluar menemui kami. Aku masih ingat,
saat itu ia menyebut serta marga keluarganya. Ya, nama marga yang tidak
asing bagi telinga orang indonesa macam aku, satu-satunya keluarga
bermarga Baswedan di desa tersebut, seperti nama seorang tokoh yang
cukup terkenal di negeriku.
Syeikh Aqil si tuan penginapan itu meminta maaf pada kami karena kamar di penginapannya sudah penuh.
“Oh, bukan itu maksud kedatangan kami ke sini?” kataku coba meluruskan kesalah-pahaman tersebut.
“Sukurlah jika memang seperti itu!” balasnya dengan logat lahm khas Yamannya.
Aku
menjelaskan maksud kedatangan kami. Syeikh Aqil sangat khidmat menyimak
bahasaku yang agak payah, sembari membelai-belai jenggotnya yang tak
lagi hitam, bahkan sudah tampak uban pada alisnya.
Beliau lalu
mengajak kami ke atas. Aku mengikutinya menaiki tangga, sedangkan si
syekh tidak ikut masih tetap di bawah. Sesampai di atap loteng kudapati
tamu-tamu penginapan sedang bersantai-santai menikmati angin malam.
Beberapa orang di saftah sebelah kiri tangga duduk melingkar, membuat
semacam riungan. Di tengah-tengah mereka tersaji cangkir-cangkir yang
kemudian aku ketahui ternyata berisi kopi bun. Syeikh Aqil
mempersilakan. “Ya, mereka lah tamu-tamu ku. Coba anda Tanya sendiri..”
“Baik Syeikh”
Dengan harapan salah satu diantaranya adalah saudara wanita yang bersama kami, aku menghampiri mereka.
“Assalamualaikum..”
“Waalaikum salam wa rahmah..”
“Afwan, apakah di antara kalian ada yang bernama Ibrahim dan Yahya?” tanyaku dalam bahasa mereka.
Mereka
tidak segera menjawab, saling pandang, berbicara sangat cepat dengan
bahasa lahm, terdengar seperti cericau burung manyar. Yang terdengar
jelas cuma ketika mengulangi nama yang kutanyakan, “Ibrahimm,.
Ibrahimm.. wa yahya.. mitsla anbiya..” ulang salah-satunya.
“Ma fi ismina Ibrahim,” jawab yang lain.
Pandanganku
terjatuh. Seketika harapanku buyar kala mendapat jawaban yang nihil.
Kasihan kalau tak sampai aku menemukan saudara perempuan itu. Kami tak
mungkin membawanya dalam perjalanan malam ini. Sialnya lagi kamar
penginapan juga sudah penuh.
“Syukran..”
Aku kembali
kepada tuan penginapan. Aku berpikir meminta tolong agar memberitahukan
kabar ini kepada semua tamu penginapan yang masih ada di dalam kamar.
Syeikh Aqil tidak berani. Pantangan baginya mengganggu pelanggan yang
sedang beristirahat, karena salah satu pelayanan yang ditawarkan
penginapannya adalah kenyamanan pengunjung. Aku coba mendesaknya,
merayunya, agar mau memudahkan. Tapi beliau masih bersikukuh. Lebih
panjang lagi, beliau menghadirkan hadits; ma yu’min bi yaumil akhir fal
yukrim dlaifahu..aku jadi tak berkutik mendengarnya.
Syeikh Aqil
menawarkan untuk datang lagi besok, kami tidak bisa, sebab kami akan
langsung melanjutkan perjalanan yang masih bermil-mil jauhnya, mengingat
waktu sewa, karena bukan mobil pribadi. Aku sudah menyerah, dan
bermaksud membawa serta perempuan itu ke Sana’a. Mungkin lewat tengah
kami baru akan sampai tempat tujuan, dan waktu yang sangat lama untuk
bersama wanita asing. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah mengambilnya,
dan aku pula sekarang yang bertanggung jawab atas keselamatan dirinya.
Ketika
turun ke lantai dua terdengar suara pintu yang dibuka. Suara tersebut
berasal dari lorong ujung. Aku meminta ijin pada Syeikh Aqil untuk
menunggu sebentar. Barangkali ada seseorang yang bakal keluar dari
kamarnya, dan tentu harapanku orang tersebut adalah Ibrahim atau Yahya.
Suara
jejakan kaki di atas lantai semakin mendekati tempatku berhenti. Lorong
yang gelap tanpa penerang membuat wujud suara itu belum juga nampak,
mungkin berasal dari kamar yang paling ujung. Antara sesaat kemudian
lelaki berbadan tegap muncul dari belik kegelapan. Aku memberanikan diri
untuk menyapa dan menghentikannya.
Betapa syukur hatiku ketika
kuketahui orang tersebut bernama Ibrahim. Lantas saja ku beritahukan apa
yang terjadi. Mendengar penjelasanku Ibrahim juga sangat senang. Ia
jabat tanganku dan menariknya kedalam dekapannya. Seperti salaman orang
pulang haji. Ia merasa bersyukur.
Aku ajak Ibrahim untuk turun ke
mobil memastikan apakah perempuan tersebut adalah saudarinya. Hampir
tiap langkahnya ia sertai dengan ucapan terima-kasihnya kepadaku. Aku
jadi tak enak sendiri dengan sifat berlebihan itu, walau pun sebagai
awam aku juga senang.
Di sudut ruang tamu si saik sudah terkapar
tak sadarkan diri. Aku mengajak Ibrahim langsung keluar menuju tempat
mobil diparkirkan. Xafi dan Umar kulihat sedang isis di atas permadani
yang sengaja mereka gelar di belakang mobil. Sedangkan penikmat daun
Ghot sudah tak bernyawa di jok depan. Pikirku juga, mungkin Umar memilih
di luar karena tidak nyaman dengan wanita asing dalam satu ruangan, dan
bagiku itu juga baik.
Ibrahim segera membuka pintu mobil untuk
menghampiri saudaranya. Kudengar dari luar mereka berdua menangis.
Barangkali adalah tangis kebahagiaan karena mereka telah dipertemukan
kembali. Aku ikut terharu. Xafi dan Umar tiba-tiba telah berdiri di
sampingku. Ibrahim keluar menemui kami, dan bilang kalau wanita itu
benar-benar saudarinya. Aku mempersilakan ia membawanya dari kami.
Kami
bertiga lalu masuk ke penginapan guna memenuhi undangannya. Lagian kami
juga perlu membangunkan si sopir yang masih tertidur pulas di ruang
tamu.
“Kami tunggu di sini saja..” ujarku ke pada Ibrahim.
“Baiklah. Mau kubuatkan kopi?” tawarnya kepada kami.
“tidak..tidak..”
serempak kami bertiga menjawab. Karena tahu, kopi yang dimaksud Ibrahim
adalah kopi bun. Ia tidak lebih manis dari jamu bagi lidah kami.
“Ya..ya,, aku tahu” sambungnya. “Kalau sahi kalian pasti suka?”
Ibrahim
mengajak saudarinya naik ke kamar meninggalkan kami. Aku membangunkan
si sopir. Kali ini aku lihat wajah Umar tak setegang sebelumnya. Ia
sudah mulai bisa tersenyum kembali. Xafi memilih berbicang-bicang dengan
Syeikh Aqil di ruang sebelah untuk menunggu. Antara beberapa saat
Ibrahim telah turun kembali menyapa kami. Sesaat kemudian disusul lelaki
lain yang nampaknya adalah Yahya, membawakan sahi dan roti untuk jamuan
kami. Aku minta umar memanggil xafi untuk ikut bergabung.
“Bagaimana ceritanya, sampai bisa terpisah dengan saudari anda?” tanyaku untuk memulai percakapan.
“Awalnya
kami pulang Haji. Dalam perjalanan di gurun terjadi badai. Kami
serombongan berpencar untuk mencari tempat berlindung masing-masing.
Badai berlangsung cukup lama dan parah menerjang kami. Saking parahnya,
apa yang kami lihat seperti dinding tampak di depan muka. Aku sendiri
berusaha menyelamatkan apa yang kami bawa, dan Yahya memegang Kendali
onta. Ya, itulah kira-kira yang terjadi saat itu. Setelah badai mereda
kami telah kehilangan Wudah. Kami terpisah sejak itu.
Aku
berusaha menacarinya tapi tak menemukan. Kami juga sudah menunggunya
lama, tapi Wudah tidak segera muncul. Mengingat perbekalan menipis, kami
memutuskan untuk singgah di desa terdekat sebelum mencarinya kembali.
Rencana besok pagi kami berangkat mencarinya. Sukurlah kalian telah
membawanya terlebih dahulu kepada kami.” Jawab ibrahim dalam bahasanya,
menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah bercakap-cakap
seantara dan telah pula menikmati jamuan kami meminta undur diri.
Sebenarnya Ibrahim meminta kami duduk lebih lama, namun kami memaksa
berangkat, mengingat perjalanan masih cukup jauh.
“Masya Allah, aku hamper lupa! Apakah saudari anda tidak berbicara selain itu?”
“Apa? Maksud anda, cara adik saya berbicara dengan menggunakan Ayat-ayat Qur’an?”
“Iya.”
“Seingatku, itu sudah lama, sekitar tujuh tahun yang lalu. Sejak itu ia tidak lagi bicara kecuali dengan ayat-ayat suci.”
“Subahanallah.. Mengapa?”
“Entahlah.. mungkin dia takut kalau hafalannya hilang!”
Ibrahim mengantarkan kami sampai mobil.
“Terimakasih.. atas jamuannya..”
“Terimakasih juga, telah membawa Wudah kepada kami..”
“Mohon doanya.. semoga selamat di perjalanan..”
“Amin.. Ma’assalamah wassahalah..”
Aku
lepaskan jabat tangan Ibrahim kemudian segera menyusul Xafi dan Umar
yang terlebih dahulu masuk. Mobil bergerak melanjutkan perjalanan.
Ibrahim tampak masih berdiri mematung melepas kepergian kami. Perasaan
menjadi lega, selega perasaan mereka.
Sekitar pukul 23: 30, mobil
yang kami naiki melintas melewati Raydah. Tidak ada yang bisa kami
lihat atas kota itu kecuali warna gelap malam dengan sedikit
pernak-pernik lampu. Sayang perjalanan antara Himr dan Raydah kami
tempuh pada malam hari. Andai saja lebih awal kami tiba, setidaknya
sebelum petang, tentu kami bisa singgah ke daerah Darwan untuk menengok
tempat Ashabul Jannah berada.
Aku dengar Umar telah mendengkur
tidur di jok belakang. Sedangkan Xafi nampaknya sedang asik
menyenandungkan kasidah-kasidah dari Diwan Hadad. Aku sendiri masih
terngiang-ngiang akan wanita mulia itu. Bagaimana bisa dia berbicara
hanya dengan ayat-ayat Al-Qur’an? Apa dia tidak bosan? Aku tak habis
pikir. Hehehe..akhlak yang sangat cantik. Walaupun aku tak sempat
melihat wajahnya, aku rasa perempuan itu mempunyai bibir yang seksi.
S
ebentar
kemudian aku tak sadarkan diri. Dan terbangun kembali ketika mobil
telah berhenti di depan sebuah penginapan di kota Sana’a. aku lihat jam
menunjukkan pukul 01.50 dini hari.
Home »
Seni Budaya
» Bibir Seksi
Bibir Seksi
Written By MWC NU SALAMAN on Sabtu, 24 November 2012 | 00.40
Related Posts
Label:
Seni Budaya


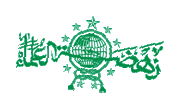


0 komentar:
Komentar Anda Sangat Kami Harapkan
Silahkan Tulis Di Kotak Yang Telah Tersedia....Terima Kasih!!